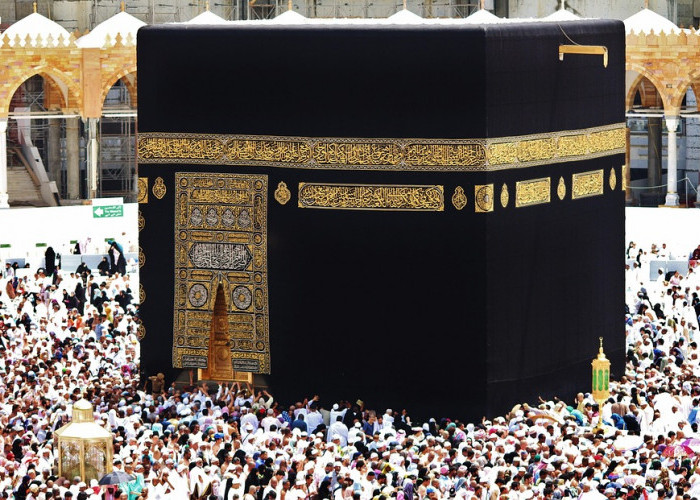Kebenaran Baru

<strong>Oleh: Dahlan Iskan</strong> "Itu sih kebenaran palsu," ujar seorang ilmuwan kedokteran dalam WA-nya kepada saya. "Tinggal sekarang mencari kebenaran yang asli," tulis Prof Dr Muhamad Nuh DEA, yang Anda sudah tahu, mantan menteri Kominfo dan menteri pendidikan di zaman Presiden SBY. Begitu banyak saya menerima respons soal video yang viral itu: cuplikan pidato wisuda saya di perguruan tinggi yang Anda sudah tahu itu. Bahkan dua guru besar sempat bikin tulisan agak panjang. Satunya khusus untuk saya. Jangan dipublikasikan. Satunya lagi sebagai koreksi terhadap saya. Bukan soal isinya. "Gejala itu sudah agak lama," ujarnya. Soal isi video ia setuju banget. Tidak ada koreksi. Sejak lama itu kapan? "Sejak munculnya metode penelitian kuantitatif," katanya. "Karena itu saya menentang adanya penelitian kuantitatif," tambahnya. Namanya: Prof Dr Hanif Nurcholis. Profesor doktor beneran. Bukan sekadar HC. Ia kini menjabat ketua Senat Universitas Terbuka. Mengajar juga di situ. Asli Demak. Lebih tepatnya, pelosok Demak. Prof Hanif pernah melakukan penelitian amat serius soal perubahan desa menjadi kelurahan. Sudah diterbitkan pula menjadi buku yang mendapat perhatian luas sampai MPR. Banyak buku tentang pemerintahan daerah dan desa ia tulis. Salah satunya buku berjudul 'Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam sistem Pemerintahan NKRI. Intinya: perubahan desa menjadi kelurahan itu merupakan pelanggaran yang serius atas konstitusi UUD 1945. Saya sudah selesai membaca buku itu. Kapan-kapan kita bahas bersama. Hari ini kita lagi bicara soal kebenaran baru. "Boleh dikata yang melahirkan 'kebenaran baru' adalah para peneliti kuantitatif," ujar Prof Hanif. "Sejak itulah ada kebenaran baru. Bukan baru lahir di zaman medsos," tambahnya. Peneliti kuantitatif, katanya, hanya meneliti persepsi responden. Bukan meneliti fakta. Fakta tidak diteliti. "Persepsi di-framing sebagai fakta lalu dimasifkan oleh buzzer menjadi kebenaran ilmiah" katanya. Ia yakin yang memasifkan kebenaran baru itu adalah para buzzer. Bahkan Prof Hanif menilai para buzzer adalah murid-murid peneliti kuantitatif persepsi. Prof Hanif sekolah ibtidaiah dan tsanawiyah di pondok terkenal di Demak: Pondok Futuhiyyah Mranggen. Sampai kelas 2 berhenti. Lalu masuk kelas 3 di SMP swasta Sultan Agung di Semarang. Lulus SMP Hanif masuk sekolah pendidikan guru, SPG –seperti istri saya. Kini jenis sekolah ini sudah tidak ada lagi. Latar belakang ekonomi keluarga di desa membuatnya tidak mampu masuk universitas. Kebetulan, tahun itu pemerintah membuka Universitas Terbuka (UT). Jadilah Hanif mahasiswa UT angkatan pertama. Ia mengambil jurusan administrasi negara. Lalu mengambil S-2 di UI dan S-3 di Universitas Padjadjaran Bandung. "Penelitian kuantitatif dengan metode survei skala Likert sebenarnya tidak meneliti apa-apa," katanya. Mereka hanya meneliti indikator-indikator konsep saja. Responden diminta pendapat sangat setuju setuju, kurang setuju, tidak setuju sangat tidak setuju terhadap indikator-indikator konsep. Prof Hanif berkarir di UT. Ia ikut berperan mengembalikan UT menjadi universitas sebenarnya. Awalnya UT hanya semacam ''event organizer'': merekrut dosen non UT untuk semacam ''buka lapak'' di UT. Setelah itu UT punya dosen sendiri. Hanif juga berperan dalam mewajibkan mahasiswa membeli modul pelajaran. Tidak lagi suka-suka. Itu bisa membuat tingkat drop out turun dari 40 persen menjadi sekitar 20 persen. Ia juga yang mengharuskan mahasiswa UT mengikuti perkuliahan secara terstruktur dan terbimbing. Tidak lagi suka-suka. Ini yang membuat kualitas lulusan UT meningkat. Hanif orang yang tekun. Juga dalam penelitian. Peneliti, katanya, jangan meneliti fakta empiris kualitas pelayanan suatu lembaga pemberi pelayanan. Itu mengakibatkan yang diteliti hanya persepsi responden. Dalam praktik Anda sudah tahu: peneliti hanya minta responden mengisi pilihan ganda: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju atas pernyataan dari indikator-indikator kualitas pelayanan. Peneliti juga tidak meneliti fakta empiris kepuasan masyarakat. Jadi, penelitian begini ini tidak meneliti fakta empiris. Mereka tidak meneliti fakta empiris kualitas pelayanan. Juga tidak meneliti fakta empiris kepuasan masyarakat. Misalnya penelitian kuantitatif soal kepuasan terhadap tempat parkir. Pertanyaan 1: Tersedia tempat parkir yang aman dan memadai. - sangat setuju - setuju - kurang setuju - tidak setuju - sangat tidak setuju Kuesioner tersebut tidak minta kepada responden memberikan informasi faktual kepada peneliti: Apakah mempunyai tempat parkir yang aman dan memadai. Kuesioner tersebut hanya minta kepada responden untuk memberi opini (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju) atas kalimat "Tersedia tempat parkir yang aman dan memadai". Lantas, dengan otak atik gatuk, pakai statistik, disimpulkanlah bahwa kualitas pelayanan (x) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat (y). "Itu yang pak Dahlan Iskan dalam bahasa satire menyebutnya sebagai kebenaran baru," ujar Prof Hanif. Kebenaran baru itu, katanya, sebenarnya kebenaran kosong. Ia dibangun berdasarkan persepsi, tidak berdasarkan fakta. Kalau pendapat Prof Hanif tersebut benar maka kita jadi tahu bahwa bapak kebenaran baru adalah pencipta penelitian kuantitatif. Kalau peneliti kuantitatif disebut sebagai guru kebenaran baru dan para buzzer sebagai muridnya terlihatlah bahwa di zaman ini murid telah lebih hebat dari gurunya. (<strong>Dahlan Iskan</strong>)
Sumber: