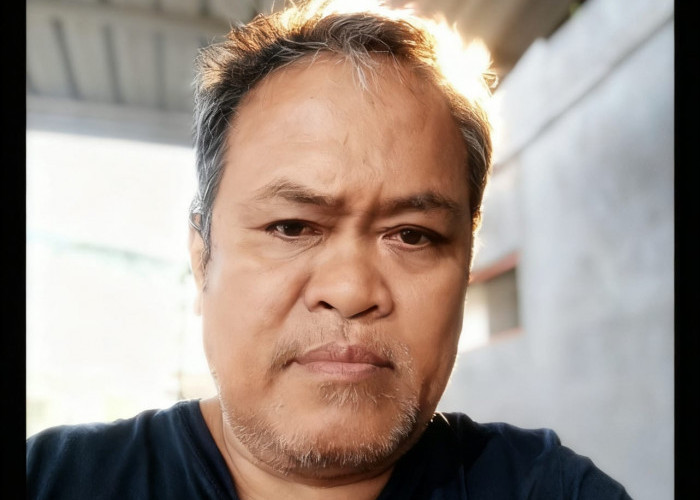Dari Dapur Ke Kota : Mengapa Saya Bersama Appi ?

--
Catatan Sosiologis-Ekologis Seorang Penggiat Ecoenzym
Oleh : Mashud Azikin
DISWAY, SULSEL - Di lorong-lorong Makassar, perubahan tidak pernah datang dengan bunyi yang keras. Ia merayap pelan, seperti aroma fermentasi dari ember ecoenzym di sudut dapur warga. Tidak mencolok, tetapi bekerja. Tidak gaduh, tetapi mengubah.
Saya belajar satu hal dari gerakan lingkungan: kota tidak berubah oleh proyek besar semata, melainkan oleh kesadaran kecil yang terus dirawat. Dan kesadaran itu, sering kali, membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya berpikir tentang infrastruktur, tetapi juga tentang manusia.
Di titik inilah saya menemukan alasan—mengapa saya harus bersama Appi.
Bagi sebagian orang, Munafri Arifuddin adalah figur politik. Bagi saya, ia adalah gejala sosiologis: tanda bahwa kepemimpinan kota mulai bergeser dari logika proyek menuju logika keberlanjutan. Dari sekadar membangun fisik menuju merawat kehidupan.
Tagline “Makassar aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan” bukan kalimat promosi. Ia seperti peta jalan. Aman berarti warga tidak hidup dalam ancaman ekologis. Tangguh berarti kota mampu berdiri di tengah krisis. Inklusif berarti yang paling lemah ikut dihitung. Dan berkelanjutan berarti pembangunan tidak mengorbankan masa depan.
Dalam pengalaman saya sebagai penggiat ecoenzym, kata “berkelanjutan” bukan konsep akademik. Ia adalah praktik: memilah sampah, memfermentasi limbah dapur, membersihkan air lindi, mengedukasi warga dari rumah ke rumah. Pekerjaan yang sunyi, tetapi menentukan.
Karena itu, ketika Appi mendorong agenda Makassar Bebas Sampah 2025, saya melihat satu hal: ini bukan lagi sekadar urusan kebersihan kota. Ini adalah upaya mengubah perilaku sosial.
Dari perspektif sosiologi, sampah adalah cermin relasi manusia dengan lingkungannya. Ia menunjukkan cara kita hidup, cara kita mengonsumsi, dan cara kita memandang ruang bersama. Kota yang gagal mengelola sampah sebenarnya sedang menghadapi krisis kesadaran.
Selama bertahun-tahun bekerja di komunitas, saya tahu: perubahan perilaku tidak bisa dipaksa. Ia harus dirangkul. Dan di sinilah peran kepemimpinan menjadi penting.
Appi tidak hanya bicara sistem, tetapi juga sisi manusia. Kebijakan iuran sampah gratis bagi warga miskin ekstrem, misalnya, adalah keputusan yang melampaui logika administrasi. Ia mengandung empati sosial. Ia mengakui bahwa krisis lingkungan sering kali berkelindan dengan kemiskinan.
Bagaimana mungkin kita menuntut warga memilah sampah, jika kebutuhan dasar mereka saja belum terpenuhi?
Demikian pula program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. Bagi sebagian orang, itu mungkin kebijakan pendidikan biasa. Tetapi dari sudut pandang sosiologis, itu adalah intervensi pada martabat keluarga. Ia meringankan beban, menghapus rasa minder, dan memberi pesan bahwa negara hadir sejak anak berangkat sekolah.
Ekologi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan keadilan sosial. Kota yang bersih tetapi warganya terpinggirkan bukanlah kota berkelanjutan. Kota berkelanjutan adalah kota yang mempertemukan keadilan sosial dan keadilan ekologis dalam satu tarikan napas.
Sebagai penggiat ecoenzym, saya melihat perubahan bukan dari podium, tetapi dari dapur warga. Dari ibu-ibu yang mulai memisahkan sampah organik. Dari anak-anak yang belajar bahwa kulit buah bisa menjadi cairan penyubur tanah. Dari lorong yang dulu bau, kini perlahan bersih.
Gerakan ini tidak besar, tetapi nyata. Dan ia membutuhkan jembatan.
Appi, dengan pendekatan kolaboratifnya, tampak mencoba menjadi jembatan itu—antara komunitas dan kebijakan, antara praktik warga dan sistem kota. Ia tidak menempatkan gerakan lingkungan sebagai proyek pinggiran, tetapi sebagai bagian dari arah pembangunan.
Di sini, saya tidak melihatnya sebagai figur tunggal yang harus dipuja. Saya melihatnya sebagai simpul: tempat berbagai energi sosial bertemu—komunitas, birokrasi, relawan, dan warga.
Dalam teori perubahan sosial, transformasi selalu terjadi ketika ada pertemuan antara kesadaran warga dan kemauan politik. Tanpa salah satunya, perubahan hanya menjadi wacana.
Mengapa saya harus bersama Appi?
Karena saya percaya kota tidak dibangun oleh mereka yang paling keras berbicara, tetapi oleh mereka yang paling konsisten merawat.
Karena saya melihat upaya mempertemukan empati sosial dan agenda ekologis.
Karena saya percaya perubahan tidak bisa hanya dikerjakan komunitas sendirian, dan tidak bisa pula hanya diserahkan pada pemerintah.
Ia harus menjadi kerja bersama.
Bersama Appi, saya melihat kemungkinan itu: gerakan ecoenzym tidak lagi sekadar aktivitas komunitas, tetapi menjadi bagian dari strategi kota. Sampah tidak lagi dilihat sebagai masalah, tetapi sebagai pintu masuk perubahan budaya.
Dan yang paling penting, saya melihat sisi manusia dari kebijakan: warga miskin yang dibebaskan dari iuran sampah, anak-anak yang berangkat sekolah dengan seragam yang sama, tanpa rasa tertinggal.
Di sanalah keberlanjutan menemukan maknanya—ketika kebijakan menyentuh kehidupan sehari-hari.
Saya belajar dari ecoenzym: perubahan besar selalu dimulai dari fermentasi kecil. Ia butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Tetapi ketika ia bekerja, hasilnya melampaui ekspektasi.
Makassar hari ini mungkin belum sempurna. Sampah masih ada. Banjir masih terjadi. Kesadaran belum merata. Tetapi arah mulai terlihat.
Dan bagi saya, berdiri bersama Appi bukan soal dukungan personal. Ini soal keberpihakan pada masa depan kota—masa depan yang aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Karena pada akhirnya, kota bukan sekadar ruang hidup. Ia adalah cermin nilai-nilai kita.
Dan setiap perubahan selalu dimulai dari satu keputusan sederhana: bersama, atau berjalan sendiri.
Sumber: