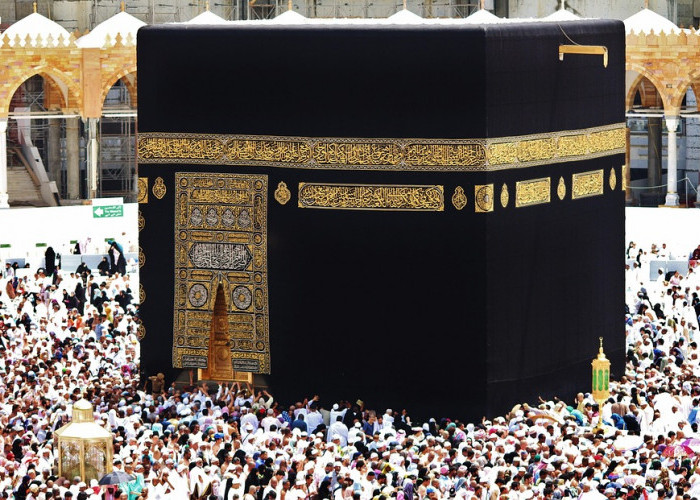Jenny Mei

Oleh: Dahlan Iskan <strong>GUS</strong> DUR yang membuat Jenny Wijaya pulang ke Indonesia. Secara tidak langsung. Dia sudah dua tahun di Beijing. Sudah mulai kerasan. Sudah kawin di sana. Mungkin Jenny tidak akan jadi pelopor mi sagu seperti sekarang kalau Gus Dur tidak jadi presiden Indonesia. Dia ikut menggerakkan masyarakat Indonesia di Beijing untuk menyambut kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid di ibukota Tiongkok itu. "Teman sekelas saya ikut saya ajak parade. Mereka orang Korea, Jepang, dan Thailand. Mereka saya minta pakai pakaian adat suku-suku di Indonesia. Saya pinjam pakaian daerah itu dari kedutaan Indonesia," ujar Jenny. Jenny ikut mengungsi ke Tiongkok akibat kerusuhan Mei 1998. Dia sendiri tidak ingin mengungsi. Tapi ayahnyi ketakutan luar biasa. Sang ayah sakit-sakitan. Kalau kerusuhan meningkat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kerusuhan Jakarta itu, Yenny tinggal di salah satu apartemen di Jalan Hayam Wuruk. Dia sudah bekerja: jualan apartemen. Dia tinggal di kamar yang belum laku. Orang tua Jenny tinggal di daerah Grogol. Suami-istri itu berbeda pendapat: sang suami ngotot harus mengungsi dari Indonesia. Sang istri tidak mau. "Saya diminta mama untuk menemani papa mengungsi," ujar Jenny. Itu hari ketiga kerusuhan Mei 1998. Mereka masih punya keluarga yang tinggal di Nanjing. Ke ibukota lama Tiongkok itulah mereka tinggal sementara. Jenny sendiri lantas ke Beijing. Dia ingin memperdalam bahasa Mandarin. Selama ini dia lancar bicara Mandarin tapi tidak bisa membaca dan menulis huruf kanji. Kemampuan bicaranya level universitas. Kemampuan membaca dan menulisnyi di level TK. Saat sekolah itulah Jenny tahu ada restoran yang makanannya enak tapi sepi sekali. Dasar orang marketing, Jenny menemui pemilik resto itu. Dia ajukan konsep agar restonya laris. Konsep diterima. Dia kerja di situ. Berhasil. Resto itu ramai sekali. Penampilan daftar menunya dia ubah total. Selama itu hanya ada tulisan Mandarin di menu. Tanpa terjemahan. Tanpa foto makanan. Jenny pun bikin brosur dalam lima bahasa: Mandarin, Inggris, Korea, Jepang, dan bahasa Indonesia. Dia sertakan foto-foto makanan yang disajikan. Dia sebar brosur itu ke mana-mana. Jenny pun kawin dengan pemilik restoran itu. Dari kunjungan Gus Dur ke Beijing Jenny tahu Indonesia mulai stabil. Gus Dur juga menyerukan agar mereka yang lari akibat kerusuhan Mei untuk pulang ke Indonesia. Jenny merayu sang suami untuk mau pindah ke Indonesia. Mau. Sang suami punya minat dalam bidang pendidikan. Ia memang dari keluarga terdidik. Ayah sang suami seorang jenderal di sana, waktu itu. Sebelum pulang ke Jakarta mereka merundingkan apa yang akan dilakukan di Indonesia. Sang suami ingin membawa teknologi pendidikan yang sudah ditemukan di Tiongkok. Yakni pulpen digital. Yang ketika disentuhkan ke tulisan bisa mengeluarkan bunyi huruf tersebut. Usaha ini lantas berkembang ke Alquran digital. "Orang Pakistan yang menyarankan mengapa tidak menjual pulpen serupa untuk membaca Quran," ujar Jenny. Jenny pun menjalin kerja sama dengan lembaga pentasbih Quran. Dia juga bekerja sama dengan banyak ustad terkenal. Jenny pun bisa mengucapkan istilah-istilah khusus terkait dengan Quran: juz, surah, tahfidz, tajwid.. Setelah era digital meluas, usaha Quran digital ini surut. "Peraturan di toko buku Gramedia juga berubah. Saya tidak bisa mengikutinya lagi," katanyi. Selama bertahun-tahun Quran digital yang dikelola Jenny ''menguasai'' rak buku Gramedia. Setelah surut itulah Jenny mulai dagang mesin pembuat mi. Juga laris. Tapi siaran TV khusus untuk jualan barang tidak ada lagi. Usaha mesin mi pun redup. Setelah Jenny punya anak tiga orang, sang suami sakit. Minta pulang ke Beijing. Meninggal di sana. "Di antara bisnis alat baca digital, Quran digital dan mesin mi mana yang paling menghasilkan?" tanya saya. "Quran digital," jawabnyi. Dari hasil berbagai usaha itulah Jenny kini punya enam ruko di Kelapa Gading, Jakarta. Enam ruko itu dia jadikan satu. Jadilah Sagolisious. Yakni restoran mi sagu pertama di Indonesia. Di situ juga konter penjualan mi sagu kering. Kerupuk sagu kering. Dan makaroni kering. Di bagian belakang resto itu dia buka music lounge: tiap malam ada live band. Banyak yang makan sambil menyanyi di situ. Waktu Pekan Olahraga Nasional (PON) diselenggarakan di Papua, Jenny ke sana. Bersama anak bungsunyi. Waktu itu ujicoba pembuatan mi dari sagu sedang dia lakukan. Dia kampanye mi sagu di Jayapura. Jenny juga ke pusat tanaman sagu di pedalaman Sorong. Berhari-hari Jenny di sana. Sampai tahu kebiasaan masyarakat di situ makan ulat sagu. Mirip orang Blora makan ulat jati. Ulat itu gemuk-gemuk. Menor-menor. Digoreng. Dimakan. Jenny ikut menikmati makan ulat sagu. Bahkan dia berani ditantang penduduk asli Papua makan ulat hidup. "Tidak menggigit lidah?" “Bagian kepalanya jangan dimakan," jawabnyi. Untuk mencapai pusat tanaman sagu itu dia harus naik perahu 6 jam. Juga harus naik sepeda motor. Tapi Jenny merasa sangat menikmati perjalanan itu. Bahkan dia kangen ingin ke Papua lagi. "Apakah kelak harga tepung sagu bisa lebih murah dari tepung terigu?" tanya saya. "Harusnya bisa. Sagu tidak perlu ditanam. Hutan sagu luas sekali. Tumbuh sendiri," ujar Jenny. "Mungkin juga tidak bisa. Untuk mengambil batang sagu harus membayar ke penduduk setempat. Tidak ada harga patokannya," tambah Jenny. Kini harga tepung sagu memang masih 50 persen lebih mahal dari terigu. Tapi kalau seluruh perusuh Disway bersatu, rasanya bisa mencari jalan keluar. Tidak logis kalau terigu lebih murah. Tapi memang banyak kan, realitas kehidupan yang tidak semuanya logis. (*)
Sumber: