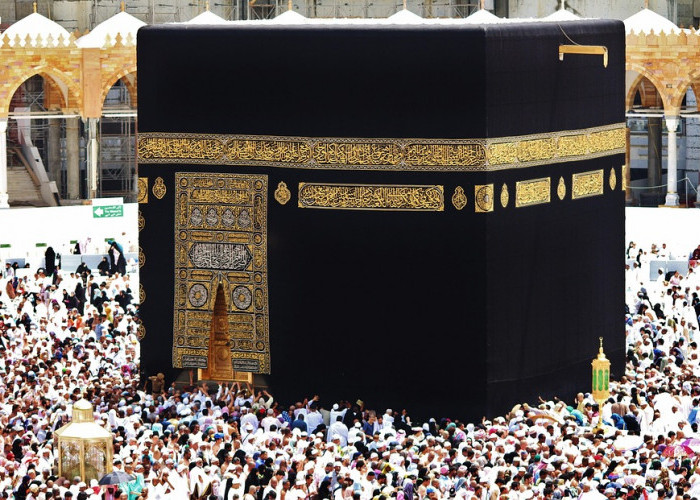Utang Emas

<strong>Oleh: Dahlan Iskan</strong> SAMPAI kemarin, soal utang emas 1,1 ton belum juga ada perkembangan baru. Saya mencoba kembali menjadi reporter: belum berhasil. Di saat masih sulit membayar ''utang tulisan'' itu ada dewi penolong. Saya memanggilnya Mbak Yani. Pernah jadi anak buah: di bagian keuangan, khususnya yang mengurus kas-bon karyawan. Bertahun tidak jumpa, tiba-tiba Mbak Yani mendaftar sebagai relawan Vaksin Nusantara. Orangnya pendiam. Kalem. Kulit bening. Rambut sebahu. Berkacamata. Suatu saat Mbak Yani kirim komentar soal artikel di Disway. Lewat WA. Mungkin baru sekali itu seumur hidupnyi menulis komentar. Saya pun membalas: kenapa tidak diposting di kolom komentar. Dia bilang singkat: malu. Merasa tidak layak. "Masih jauh dari komentar-komentar dari pembaca Disway yang lain," jawab Mbak Yani. Saya pun minta dia terus menulis. Saya lihat tulisannya kian baik. Sekali waktu saya tampilkan di Disway. Kian lama Mbak Yani kian sering menulis. Dikirim ke WA saya. Belum juga berani ke kolom komentar. Suatu saat saya memanggilnyi ''Bu Yani". Langsung saya kena K.O: "tiba-tiba saya merasa tua", tulisnyi. Sejak kena K.O. itu saya harus ingat untuk memangilnyi Mbak Yani. Agar hari ini Disway berisi tulisan tentang emas, maka saya muatkan tulisan Mbak Yakni ke WA saya –tanpa izin beliau. Cobalah para perusuh menilai: layakkah masuk kolom komentar. Siapa tahu, kalau perusuh yang mengatakan beliau lebih pede. Inilah tulisan Mbak Yani.<strong>(Dahlan Iskan)</strong> *** Kolom komentar Disway dua hari ini berisi tentang pengalaman dan lelucon seputar logam emas. Kalau begitu saya juga mau ikut nimbrung. Begini: Dulu saya membeli anting-anting berbentuk buah stroberi. Untuk anak saya, ketika dia masih kecil. Dan liontin permata untuk ibu saya. Namanya juga anak-anak, anting-anting itu hilang satu. Saya pun kembali ke toko emas di Pasar Kebayoran Lama dengan maksud untuk tukar tambah. Ternyata tidak semudah itu. Emas itu harus dijual dulu dengan nilainya yang rendah. Sangat tidak masuk akal. Itu karena anting-anting yang tinggal sebelah dianggap barang rongsok. Saya masih berargumen dengan hitung-hitungan saya, tapi itu tidak berguna. Caranya melayani pun dengan tidak ramah, sangat berbanding terbalik ketika melayani saya sebagai pembeli. Lihatlah caranya menolak, ia bilang, "coba saja ke toko lain". Saya pun ke toko di sebelahnya, sama. Akhirnya saya relakan saja, berapa pun nilai yang dia mau bayar. Tentang liontin permata untuk ibu, itu saya beli di Thailand. Ke sana ketika mendapat hadiah <em>grand prize</em> dalam acara kantor. Bersama Mas Nanang Prianto sekeluarga. Ia juga menerima hadiah <em>grand prize</em> di kantor Surabaya. Saya dan anak saya diajak ke salah satu destinasi wisata, ke sebuah tempat yang dibuat seolah-olah lokasi penambangan emas. Kami dibawa menyusuri lorong bawah tanah, menyaksikan diorama bagaimana penambang emas itu bekerja dengan segala kesulitan dan risikonya. Juga cara bagaimana batuan emas itu diolah, dimurnikan dengan tungku panas. Kami tahu melalui narasi yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Di kereta yang membawa kami ada tombol pilihan bahasa apa yang mau kami dengar. Sekeluarnya dari lorong gelap itu, kami diperlihatkan bagaimana cara perajin emas bekerja. Dari balik kaca. Saya mengamati betapa sulitnya perhiasan itu dibentuk, pun sekadar sebuah cincin yang sederhana. Jadi memaklumi mengapa dalam transaksi pembelian emas ada yang diperhitungkan sebagai ongkos. Setelah melihat pandai emas itu bekerja, kami diarahkan ke suatu tempat. Area itu luas, terang benderang dengan cahaya lampu. Kilauan emas dan permata terpancar dari dalam etalase kaca. Itulah toko emas terbesar yang pernah saya lihat. Seorang pramuniaga pria, menggunakan bahasa Indonesia menyambut kami dengan ramah dan menggiring saya ke salah satu etalase. Saya tertarik pada sebuah liontin permata. Saya teringat ibu. Harga perhiasan itu tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Apalagi sebagai pemenang <em>grand prize</em> saya juga mendapatkan uang saku. Kebetulan harga perhiasan itu setara dengan uang saku yang saya dapatkan. Tanpa pikir panjang, saya membelinya. Hebat benar ya pramuniaga ini, bisa menebak isi kantong eh dompet saya.. ha ha. Prosesnya lama, liontin permata itu dibawa masuk ke dalam oleh pramuniaga tadi. Katanya mau difoto dan dibuatkan sertifikat. Saya bertanya, "apakah emas ini bisa dijual kembali di Jakarta?". Lalu Ia menjawab "untuk apa beli kalau untuk dijual lagi? "Maksud saya, apakah emas ini laku dijual di tempat lain? Bisa, ia hanya menyebutkan satu daerah di Jakarta-Glodok. Saya tidak tahu apakah pada saat itu istri Mas Nanang –Mbak Tari– juga terjebak membeli seperti saya, tidak sempat saya tanyakan. Belakangan ibu saya mendatangi sebuah toko emas di Depok. Beliau bermaksud untuk menjual perhiasan itu sekaligus memastikan apakah emas yang dilengkapi sertifikat itu laku dijual. Ternyata tidak laku. Beliau tunjukkan sertifikat pembeliannya. Juga tidak ada pengaruhnya. Kadar emasnya tidak sesuai kriteria. Permata yang terlihat berkilau itu hanya aksesori yang bernama zirconia. Tidak menyerah, ibu ke toko yang lain. Juga tidak mau terima. Puji Tuhan, seorang inang-inang yang duduk di emperan toko emas itu menjadi penolong. Dia mau membelinya dengan harga Rp 800.000. Tidak mau lebih. Permatanya dilepas saja. Tidak berharga. "Ini hanya serpihan seperti kaca," katanya. Bagi saya, memiliki ''emas'' ternyata bukan sebuah investasi. Mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000 bukanlah suatu penyesalan. Saya menganggap itu sebagai sebuah pembelajaran yang berharga. *** Pun pembelian emas Antam 6 ton oleh pengusaha Surabaya itu juga sebuah pembelajaran. (*)
Sumber: