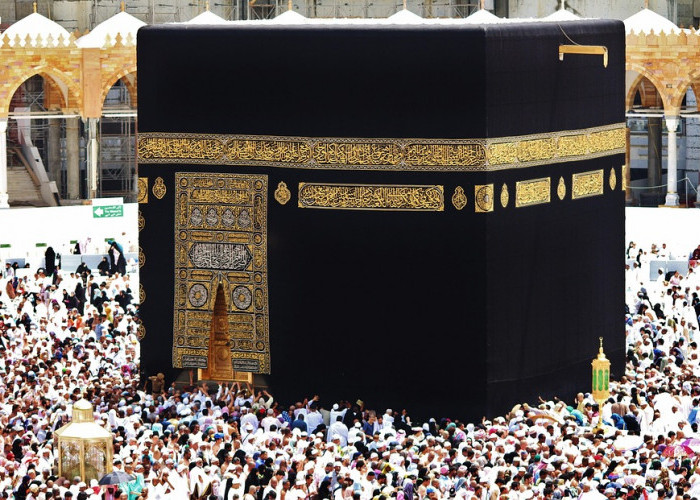Depan Belakang

<strong>Oleh: Dahlan Iskan</strong> ''PILIH yang mana?'' Saya diminta masuk ke dalam <em>counter check in</em>: agar bisa melihat layar komputer di meja petugas. Ada denah susunan kursi di layar itu. Banyak kursi sudah terisi. Saya memang telat <em>check in.</em> Tidak ada lagi dua kursi kosong yang bersebelahan. Saya harus duduk terpisah dari istri. Sedih. Padahal maunya meniru Putu Leong: lengket terus seperti prangko. Gara-gara telat <em>check in.</em> Yang disebut ''telat'' di zaman sekarang itu sebenarnya masih dua jam dari waktu <em>boarding</em>. Dulu, <em>check in</em> dua jam sebelum <em>boarding</em> itu disebut <em>early check in</em>. Sekarang dikategorikan telat. Yang disebut ''tidak telat'' adalah check in online: bisa 12 jam sebelumnya. Bisa pilih tempat duduk prangko. Mengapa saya tidak bisa <em>check in online</em>? Itu gara-gara nama saya tidak sama. Antara yang di visa dan di paspor. Itu tidak bisa diterima di sistem komputer <em>check in online</em>. Saya tegur teman saya yang mengurus check in online: kenapa tidak dijelaskan ke komputer itu. Bahkan kenapa tidak didebat: beda nama itu bukan salah saya. ''He he komputer tidak bisa didebat, Pak Boss,'' jawabnyi lantas senyum-senyum. ''Jangan panggil saya Pak Boss lagi. Saya sudah bukan bos,'' tegur saya. Pun nama istri saya. Ada tambahan kata ketiga. Di visa nama saya jadi Dahlan Iskan Mochamad. Istri saya jadi Nafsiah Sabri Shahdan. Saya sempat sewot dengan tambahan itu. Pura-pura. Kenapa tidak minta izin saya dulu. Tiba-tiba saja berubah: sejak umrah tahun kapan itu. Kata mereka: nama harus tiga kata. Oke. Tapi kalau pun begitu saya akan pilih Dahlan Iskan bin Iskan. Pun istri saya. Kenapa nama ketiganya tidak pakai kata Dahlan: Nafsiah Sabri Dahlan. Dia kan istri saya. Lalu saya bentak istri saya, dalam hati: hayo, siapa ini Shahdan. Anda pernah kawin sebelum dengan saya ya? Istri saya ketakutan: juga dalam hati. Dia sendiri merasa aneh. Biasanya kan saya yang ketakutan. Ternyata Shahdan itu nama kakeknyi. Yang pekerjaannya tukang angkut barang di gerobak dorong. Di Samarinda. Masa kecil istri memang ikut kakek. Istri saya anak pertama dari 12 bersaudara. Ayahnyi tentara. Pergi terus. Ke medan tugas. Ibunyi urus adik-adiknyi. Visa Arab Saudi tidak menempel di paspor. Visa itu dikirim lewat email. Maka email itu pun saya minta di-<em>print</em>. Siapa tahu ada masalah di bandara nanti. Saya pun ke bandara lebih awal. Siap-siap kalau ada masalah. Juga berharap masih ada kursi prangko. Begitu tiba di <em>counter s</em>aya sodorkan dua paspor. Juga dua lembar visa. Tidak ada pertanyaan apa pun. Petugasnya lebih ''mengerti'' soal beda nama itu. Orang lebih punya perasaan dibanding online. Komputer bekerja berdasar data. Manusia bisa berdasar pengalaman. Satu-satunya persoalan di <em>check in</em> tinggal itu tadi: kursi prangko. Untuk jurusan Jakarta ke Abu Dhabi saya dapatkan kursi itu. Tapi Abu Dhabi ke Jeddah harus pisah. Saya pura-pura marah ke petugas check in. Sekadar agar terlihat oleh istri bahwa saya serius berusaha. Lebih baik marah ke petugas daripada dimarahi istri. Memang istri saya tidak pernah ngata-ngatai saya ''goblik'' atau ''comberan'' tapi dari ekspresi kecilnyi saja saya sudah bisa menebak pedalaman hatinyi. Dari layar komputer petugas itu saya baru tahu: kini ada kabin pesawat yang susunan tempat duduknya belum pernah saya lihat. Separo kursinya menghadap ke belakang. Selang seling. Bukan seperti di beberapa kereta komuter: separo menghadap ke depan, separonya lagi ke belakang. Ini beda. Pesawatnya Boeing 787 Dreamliner. Baris pertamanya: 1-2-1. Dua kursi yang di tengah itu menghadap ke depan. Di situlah saya dan istri. Untuk Jakarta-Abu Dhabi. Satu kursi di kiri dan satu kursi di kanan menghadapnya ke belakang. Baris keduanya terbalik: susunannya tetap 1-2-1, tapi posisi hadapnya kebalikannya. Lalu baris ketiga seperti baris pertama. Baris keempat seperti yang kedua. Begitu sampai baris keenam. Efisiensi. Perdebatan di antara ahli desain rupanya tidak pernah berhenti: kursi harus diatur bagaimana. Agar dengan pesawat yang sama bisa menampung kursi lebih banyak. Dengan cara cerdas. Bukan sekadar menyempitkan jarak tempat duduk seperti di pesawat merah di Indonesia. Sekitar 20 tahun lalu saya juga mengalami hal baru: jurusan Hong Kong. Cathay Pacific. CX. Posisi kursinya dibuat mencong. Tidak menghadap ke depan. Tapi juga tidak menghadap ke samping atau ke belakang. Kursi itu menghadap ke sudut kira-kira 40 derajat. Kursinya tetap bisa dibuat flat tapi terasa lebih sempit. Saya masih bisa menerima. Ukuran badan saya masih bisa fleksibel. Beberapa kali saya terbang dengan susunan kursi seperti itu. Tapi kreasi CX tersebut kelihatannya tidak membawa sukses. Dihentikan di situ. Tidak ada penerbangan lain yang meniru. CX sendiri terlihat tidak mengembangkannya ke pesawatnya yang lain. Naskah ini saya tulis di pesawat jurusan Jakarta ke Abu Dhabi. Jam 04.00 waktu pesawat. Istri saya lagi terlelap di sebelah. Lengket dengan selimut tebalnyi. Saya naikkan penyekat otomatis yang memisahkan tempat tidurnyi dengan kursi saya. Kalau pun mendadak terbangun dia tidak akan bisa marah melihat saya lagi menulis tentang dirinyi. Tiba-tiba dia ketok-ketok dinding tipis penyekat itu. ''Kok ditutup?'' katanyi. Saya pun mengakhiri tulisan ini. Saya pun menurunkan pemisah tipis itu. Tinggal pijit tombol. Lebih mudah pijit tombol sekali daripada mengetuk tiga kali. Soal tambahan nama tadi sebenarnya harus saya syukuri. Waktu kecil nama saya memang pakai Mochamad. Moch Dahlan. Dimulai dengan huruf M. Terlalu jauh di belakang. Kalau kata pertama D, jadinya di urutan keempat. Lalu, agar puitis, saya tambahkan nama bapak saya. Jadilah Dahlan Iskan. Enam bulan lalu saya mendapat tamu: ahli hongsui terkait dengan logo dan nama. Ia mengatakan nama depan saya itu yang membuat saya gagal jadi calon presiden. Posisi huruf ''h'' yang di tengah itu penyebabnya. Sang tamu menyarankan perbaikan nama. Ada dua cara: Dahlan diubah menjadi Dhalan. Atau: ditambah kata Mochamad di depannya. <strong>(DAHLAN ISKAN)</strong>
Sumber: