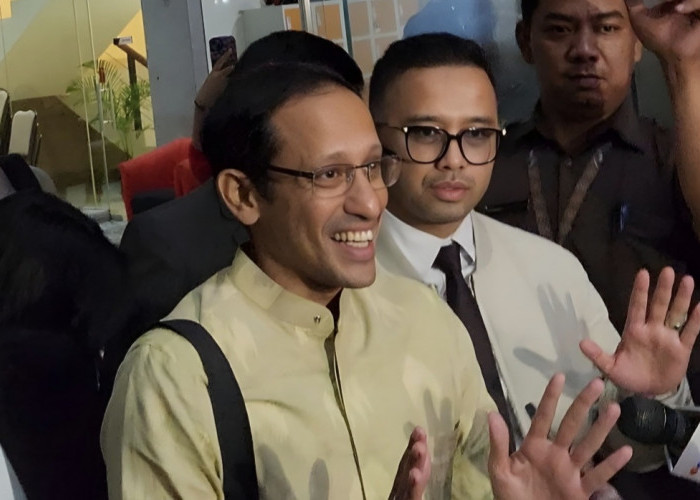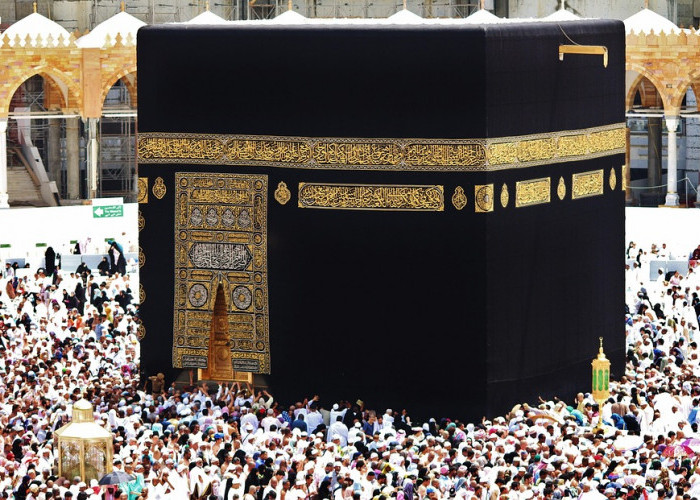Pilkada di Antara Politisi dan Selebriti
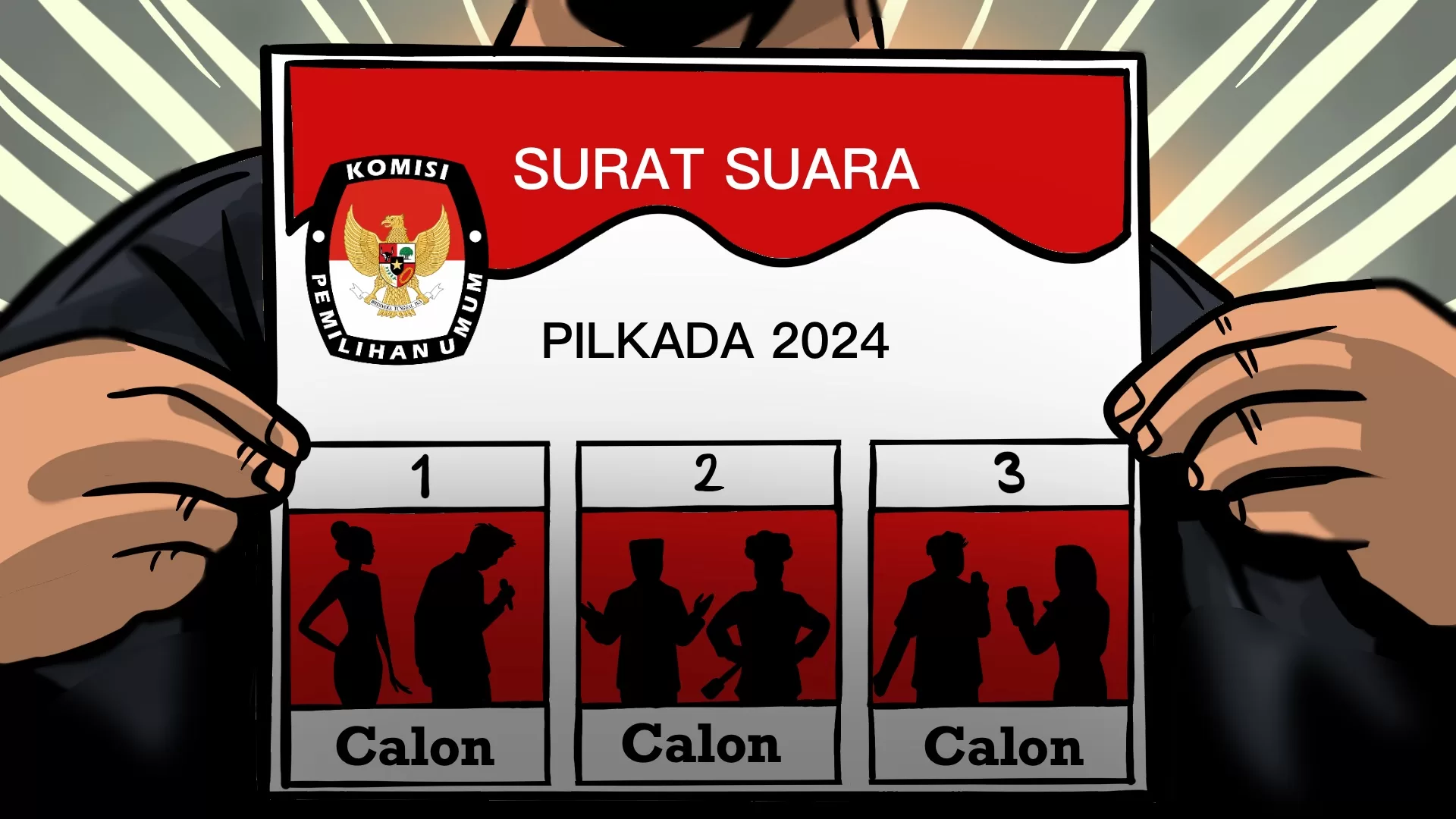
<strong>Oleh: Sukarijanto, Direktur di Institute of Global Research</strong> ERA REFORMASI menjadi awal dari adanya kebebasan berekspresi yang berdampak positif bagi masyarakat dan perkembangan industri media massa di Indonesia. Penyajian informasi dalam media sangat membutuhkan figur publik sebagai orang yang menjembatani antara media dan masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat dipahami. Di sanalah peran seorang tokoh atau orang terkenal dari kalangan artis (selebritas) mengisi ruang publik. Tujuannya, menarik minat rakyat atau mengikuti selera pilihannya. Kondisi itu dimanfaatkan partai politik dalam meningkatkan jumlah suara pada pelaksanaan pesta demokrasi, baik pilpres, pileg, maupun pilkada. Kepopuleran seorang tokoh dalam media seolah segala-galanya untuk masyarakat yang sebagian besar tingkat pendidikannya menengah ke bawah. Begitulah dalam pelaksanaan demokratisasi, seakan masyarakat hanya mengandalkan informasi yang disajikan media dengan para selebritas atau pesohor sebagai endorser. Fenomena hadirnya beberapa artis dalam perpolitikan Indonesia kerap kali tanpa diimbangi dengan proses pendidikan politik. Dengan demikian, masyarakat dalam menentukan sikap berdasar kapabilitas para calon yang akan dipilih secara profesional sangat minim literasi. Partai politik (parpol) sebagai salah satu lembaga yang turut bertanggung jawab terhadap proses pendidikan politik bangsa harus memiliki sistem yang jelas dalam pembentukan kader parpolnya sehingga partai dapat melahirkan para caleg profesional dan bukan berdasar popularitas atau kekayaan semata. Memang tak ada yang salah dengan partai politik yang merekrut tokoh populer dari kalangan artis untuk didaftarkan jadi calon anggota legislatif (caleg). Akan tetapi, langkah itu akan bermasalah jika seorang calon tak dipersiapkan dengan matang dan sekadar dicalonkan atas tujuan meraih suara instan untuk parpolnya. Pada hajatan pilkada 2024 sebentar lagi, baik pemilahan bupati (pilbup), pemilihan wali kota (pilwali), maupun pemilihan gubernur (pilgub), banyak partai politik yang mengusung artis atau selebritas sebagai calon. Para artis atau selebritas itu datang dari berbagai kalangan seperti pemain sinetron, presenter televisi, chef, musisi, model, atlet, selegram, pendakwah, maupun pelawak. Memang diakui bahwa aspek popularitas merupakan nilai tambah bagi para selebritas dan modal dalam komunikasi politik. Para artis yang sering tampil pada acara televisi, baik sebagai pemain sinetron maupun pembawa acara, menyebabkan para artis tersebut menjelma bak megnet yang menarik para fans atau penggemar. Dengan demikian, hal tersebut memudahkan para artis untuk dikenal masyarakat dan menggaet para konstituennya. Jadilah sang artis sebagai vote getter andalan parpol. Menurut hasil riset Populi Center, pada 2009, persentase kursi selebritas di DPR sebesar 3,2 persen. Jumlahnya turun menjadi 2,8 persen pada Pemilu 2014. Persentase itu kembali menurun menjadi 2,4 persen pada Pemilu 2019. Menurut Syamsuddin dalam jurnalnya, Caleg Artis, So What (Mei 2013), basis kompetisi dalam pemilu legislatif sejak 2009 adalah popularitas figur para caleg yang diajukan partai politik dan kemampuan finansial yang sangat berperan. SANDIWARA POLITIK ATAU POLITIK SANDIWARA? Sistem politik yang dibalut dengan asas kapitalisme dewasa ini lebih mengandalkan ketenaran dan modal gede ketimbang kapabilitas para calon anggota legislatif sehingga caleg artis dan pesohor memperoleh peluang lebih besar dalam memperoleh dukungan publik. Sebaliknya, peran meritokrasi sebagai wadah atau lembaga pengaderan calon anggota legislatif agar terbentuk kader berkualitas kian terpinggirkan. Fenomena caleg artis merupakan salah satu gejala kaderisasi partai yang tergradasi kalau tidak bisa dikatakan gagal. Sebaiknya kehadiran parpol dapat memberikan pendidikan politik, kaderisasi, dan seleksi kepemimpinan secara berskala serta demokratis. Pada fase itu, partai politik tidak perlu membutuhkan kehadiran caeg dari kalangan artis. Pencalonan para selebritas atau pesohor menjadi anggota legislatif realitasnya merupakan cara mudah dan instan sebuah partai politik untuk mendongkrak suara atau kursi di parlemen. Bagi parpol yang punya nafsu besar meraih kursi di DPR dan DPRD untuk bisa lolos syarat ambang batas parlemen, mengusung orang yang punya potensi besar dipilih itu akan lebih baik ketimbang mengangkat kader sendiri meski senior tapi ”tidak layak jual”. Faktanya, banyak anggota legislatif yang berasal dari kalangan artis tidak cukup menonjol dari anggota lainnya yang berasal dari nonartis, khususnya dalam mengemukakan gagasannya dan melakukan advokasi di parlemen. Kalangan artis sangat terkesan lebih memainkan peran ”sandiwara politik” ketimbang berperan sebagai wakil rakyat sesungguhnya. Jadi, sebetulnya publik dirugikan dengan kehadiran caleg artis. Sebab, kemampuan mereka sebagai politisi atau yang berkaitan dengan legislasi masih ”jauh panggang dari api”. Kemampuan mereka memang sudah teruji di panggung menyanyi, main film, dan melawak. Tetapi, di saat yang bersamaan, mereka harus dituntut memiliki kapasitas sebagai seorang politikus atau legislator yang mumpuni memperjuangkan nasib rakyat. Realitasnya yang terjadi, mereka terkesan gagap mengakomodasi pernik-pernik permasalahan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Terdapat beberapa alasan mengapa banyak artis dan pesohor mau nyaleg. Pertama, sangat bisa jadi mereka tertarik dengan isu-isu sosial-politik. Mereka mungkin melihat masuk ke jalur politik sebagai wahana membuat suatu perubahan. Sebagai artis, mereka punya modal kemampuan yang unik untuk bisa menginspirasi, memotivasi, dan memengaruhi orang lain melalui karyanya. Selain itu, para selebritas yang punya banyak pengikut di media sosial bisa menggunakan platform yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting di samping bisa digunakan untuk mengampanyekan suatu perubahan kepada para pengikutnya. Kendati popular di mata masyarakat dan terkenal di kalangan luas, belum tentu ada jaminan artis yang mencalonkan diri itu pasti berhasil. Bahkan, banyak juga yang malah dibanjiri kritik karena kurangnya pengalaman politik dan kepekaan sosial. Atau, cuma dengan bermodal status selebritas, mereka berharap bisa mendapatkan banyak suara. Kedua, ada keyakinan mereka mampu membawa perspektif baru dan berbeda di dunia politik. Beberapa dari mereka ada yang cukup tertarik dengan isu-isu di masyarakat seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di industri kreatif, mereka terbiasa berpikir di luar kebiasaan yang diharapkan mampu menghasilkan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang kompleks. Ketiga, mereka punya keyakinan untuk melibatkan dan menginspirasi pemilih yang terhubung dengan orang-orang secara personal, sekaligus punya potensi menggugah minat pengikutnya untuk terlibat di dalam politik. Itu terutama berlaku untuk generasi muda umumnya yang memiliki keterlibatan minim dalam dunia politik. Dengan mencalonkan diri, para artis itu bisa membawa energi dan antusiasme baru ke dunia politik. Sebaliknya, tantangan parpol dalam mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan yang kian ketat tentunya membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Maka, satu-satunya cara praktis dengan hasil instan untuk menghidupi kelangsungan partainya adalah ”memperjualbelikan konsesi politik” (baca: mahar) yang bernilai ratusan juta bahkan miliaran kepada pesohor dan artis yang bermodal gede untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari partai. Ekosistem politik yang dibangun dengan mengabaikan asas meritokrasi kelak cenderung melahirkan legislator kualitas pesohor nirprestasi. (Sukarijanto)
Sumber: